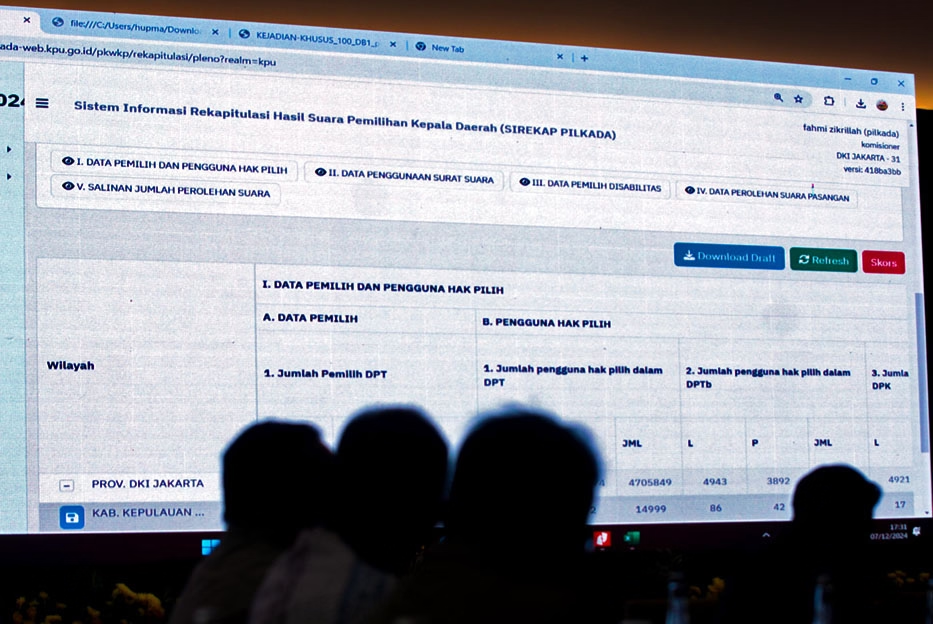Eramuslim.com – Ketika Undang-Undang Perkebunan, Minerba, hingga proyek strategis nasional food estate dirumuskan, tak satu pun makhluk hidup selain manusia dilibatkan. Tidak ada harimau, orangutan, gajah, atau pohon yang diundang menyampaikan pendapat. Nasib ikan dan terumbu karang pun tak pernah diperhitungkan saat izin tambang diberikan.
Inilah kerangka pikir yang ingin digugat oleh Robertus Robet dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Filsafat Sosial Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Dalam pidato bertajuk “Dari Emansipasi ke Ekosipasi“, Robet menawarkan satu gagasan radikal: alam harus diakui sebagai subyek politik dan hukum, bukan sekadar obyek eksploitasi.
Ekosipasi: Membebaskan Alam dari Status Obyek
Robet memperkenalkan istilah ekosipasi, sebuah bentuk pembebasan ekologis. Gagasan ini menempatkan seluruh ekosistem—hewan, tumbuhan, sungai, udara, hingga gunung—sebagai entitas yang memiliki hak dan martabat, bukan hanya manusia.
“Kalau robot dan perusahaan bisa diakui sebagai subyek hukum, mengapa alam yang menopang seluruh kehidupan masih diperlakukan sebagai barang?” ungkap Robet.
Ia menyoroti bagaimana paradigma hukum selama ini hanya mengakui manusia dan entitas buatan manusia (seperti PT atau yayasan) sebagai subyek hukum. Bahkan Undang-Undang Lingkungan Hidup pun, meski mengakui hak hukum alam, tetap menempatkannya sebagai obyek yang dibela oleh manusia—bukan pembela haknya sendiri.
Saatnya Alam Duduk di Meja Perundingan
Gagasan Robet menantang sistem hukum dan politik yang masih antropo-sentris. Ia mendorong agar alam diakui sebagai pihak yang punya hak konstitusional, bisa menyampaikan aspirasi, bahkan menolak kebijakan yang merugikan.
Lantas, bagaimana caranya “mengundang” pohon dan ikan ke rapat kebijakan publik?
Robet menjelaskan, seperti anak-anak atau penyandang disabilitas berat yang diwakili oleh wali hukum, alam pun bisa diwakili oleh “pengampu”: masyarakat sipil, lembaga lingkungan, bahkan pengadilan.
“Kita butuh jembatan suara alam. Kalau buruh dan pengusaha punya perwakilan, mengapa tidak pohon, sungai, dan udara?” tegasnya.
Robet juga mengajak negara belajar dari kearifan masyarakat adat. Komunitas Baduy di Banten, misalnya, selalu bermusyawarah dengan alam sebelum mengambil keputusan. Alam bukan hanya dihormati, tapi diajak bicara.
Masyarakat adat, menurut Robet, telah lebih dulu mempraktikkan ekosipasi melalui prinsip keseimbangan dan penghormatan.
“Sudah saatnya kita berhenti menganggap mereka sebagai kelompok ‘tertinggal’. Justru mereka yang bisa menjadi guru kita,” kata Robet.
Tantangan Besar: Hukum, Politik, dan Kapitalisme
Meski menarik, gagasan ini bukan tanpa tantangan. Jika alam diakui sebagai subyek hukum sepenuhnya, maka tanah, sungai, dan sumber daya tak bisa lagi dimiliki atau dijual seenaknya. Paradigma ekonomi dan investasi harus berubah total.
Robet menyindir bagaimana kapitalisme bahkan telah mengobjekkan manusia, dengan sistem alih daya dan tenaga kerja yang diperdagangkan. Maka, tak heran alam pun terus-menerus dieksploitasi tanpa pertimbangan etis.
Namun, Robet menegaskan, perubahan ini adalah keniscayaan, bukan utopia. Krisis iklim dan kerusakan lingkungan hari ini menjadi bukti bahwa sistem hukum dan politik yang ada telah gagal mendengar suara alam. Pidato Robertus Robet bukan sekadar refleksi akademik. Ini adalah seruan etis dan politik: sistem hukum dan demokrasi Indonesia harus bergerak dari emansipasi manusia menuju ekosipasi semesta.
Alam bukan hanya “dipertimbangkan” dalam kebijakan. Ia harus diakui, dilibatkan, dan dihormati. Karena masa depan manusia tak bisa lepas dari nasib bumi tempatnya berpijak.
Sumber: Tempo.co